KELUARGA
DALAM PRESPEKTIF BUDAYA LERAGERE
Oleh
: Marselinus B. Lewerang
*) Disajikan pada forum diskusi masyarakat
etnis
Pandangan Umum
No
man is an island, Tak
ada manusia yang ingin hidup menyendiri, sama seperti sebuah pulau terpencil
tak berpenghuni. Manusia secara kodrati harus hidup bersama dengan manusia lain.
Ini merupakan hukum yang membentuk
manusia sebagai homo socion atau
makhluk sosial. Hukum ini pulalah yang mendorong terbentuknya sebuah keluarga.
Pada kesempatan diskusi ini mari kita kaji
lebih jauh tentang “keluarga” dalam psepektif budaya leragere. Apa dan
bagaimana konstruksi keluarga yang adaptif terhadap lingkungan lokal, taat asas dan mempedomani nilai-nilai positif
budaya setempat harus bisa digali dan dirumuskan kembali dalam bentuk
kesepakatan bersama.
Keluarga menurut Sosiolog Duvall Dan Logan
(1986) merupakan sekumpulan orang
dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk
menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental,
emosional serta sosial dari tiap anggotanya. Dalam dokumen Departemen Kesehatan RI (1988) Keluarga
didefinisikan sebagai unit terkecil masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga
dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu
atap dalam keadaan saling ketergantungan. Secara lebih tegas UU.
No. 10 Tahun 1992 menetapkan batasan keluarga mencakup suami-istri atau
sumi-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Perlu
diingat bahwa batasan UU ini ditetapka hanya dengan tujuan untuk memudahkan
pelayanan negara
Sebagaimana budaya lamaholot
pada umumnya orang Leragere cendrung
memandang kelurga secara geneologis (hubungan darah) dalam skop yang lebih
luas. Cakupan Sebuah Keluarga tidak hanya terbatas pada ayah, ibu dan anak saja
tetapi juga termasuk kerabat lain seperti kakek, nenek, saudara, paman dan
keponakan. Nampaknya budaya Leragere menganut
prinsip kekerabatan tanpa batas. Ini merupakan sebuah senjata ampuh
untuk melawan sikap individualistik sekaligus tantangan dalam memajukan
kesejahteraan keluarga.
Individualistik menurut Watson & Morris (2002)
merupakan sikap yang dimiliki individu
yang cendrung mengisolasi diri dari masyarakat. Sikap seperti ini berdampak
buruk terhadap perkembangan struktur sosial serta toleransi antar sesama. Dalam
perkembangan masa kini individualistik
dicatat sebagai salah satu dampak pergembangan global yang bisa menghancurkan
peradapan. Dengan demikian maka individualistik termasuk gejala perkembangan
yang harus dihilangkan. Apa gunanya maju kalau pada akhirnya yang didapat cuma sebuah
kesendirian
sama seperti pulau terpencil tak berpenghuni. Bila kebersamaan dibangun mulai
dari keluarga maka akan terbentuk sistem sosial yang kuat dengan mengedepankan
nilai-nilai positif budaya lokal.
Keluarga
dan Sistem Sosial
Sistem
sosial Leragere tidak mengenal strata atau pembedaan tingkat sosial. Meski ada
penggunaan istila kebelang, tetapi
ini lebih diarah pada penghuni pertama kampung yang disebut tanah rala atau tuan tanah. Hak tuan
tanah terlihat pada tata ritual
penyembelihan hewan korban. Dalam ritual penyembelihan ini suku tuan tanah
bertugas sebagai pemegang kepala. Terkait ini maka nama suku tuan tanah pada beberapa
kampung disebut eteng atau tarang. Sesuai tradisi suku tuan tanah
tidak otomatis menjadi kepala kampung karena biasanya pemegang jabatan ini dipilih
langsung melalui musyawarah mufakat.
Jauh
sebelum masuknya agama dan terbentuknya NKRI orang Leragere sudah berhasil
menerapkan dengan baik asas kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, merdeka, persatuan dan kesatuan, kedaulatan rakyat, dan adil makmur. Tentang ini bisa digali melalui
beberapa situs budaya animisme seperti
nuba, bohpong, o’e, ba’sa dan naming.
Keluarga Leragere
tempo dulu sudah percaya bahwa ada kekuatan dan kuasa maha besar yang
menjadikan serta memelihara semua yang ada di alam semesta ini. Langit dan bumi
adalah hasil karyanya. Sebagaimana suku lamaholot pada umumnya orang leragere percaya bahwa manusia terbentuk dari
perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Benih kelamin laki-laki dilukiskan
sebagai kekuatan lera wulan,
sedangkan benih kelamin perempuan merupakan kekuatan tanah ekan. Oleh karena itu maka penguasa atas alam semesta disebut Lera
Wulan Tanah Ekan. Secara fisik dinyatakan dengan tugu batu yang disebut nuba. Biasanya nuba ditanam berdapingan
dengan sebuah batu ceper yang dinamakan nara
(B. K. Koten, 1983).
Lahir anak
laki-laki atau perempuan dalam sebuah keluarga tidak bisa ditentukan oleh
manusia. Hanya Sang Maha Kuasa sendiri saja yang memiliki kewenangan ini. Ada
keluarga mungkin bisa melahirkan anak laki-laki dan perempuan, ada yang hanya
anak perempun, atau laki-laki saja,
bahkan ada yang tidak mempunyai keturunan. Misteri tersebut kemudian menjadi
alasan terbentuknya hukum adat terkait belis perkawinan yang dikenal dengan sebutan : Bi’neng mapang La’meng (Anak perempuan
suku menanggung belis anak laki-laki suku). Hukum tersebut bisa diterapkan
dengan baik bila ada kesepahaman atas filosofi Bi’neng su’u, La’meng su,u (semua anak baik perempuan maupuan laki-laki adalah milik dan tanggungjawab
suku). Sikap ego dan Ketidak sepahaman
atas filosofi ini sering menimbulkan perseteruan antar keluarga dan kerabat
suku.
Orang Leragere
yakin bahwa tanah kelahirannya merupakan warisan
turun temurun bukan hasil rampasan. Tentang keyakinan ini terungkap
melalui penggalan syair : Lewu tuang sar’ang
ulung; tanah nuba nara; ina tau ama gopa. Artinya Leragere adalah kampung
lama titipan para leluhur, bukan hasil
rampasan milik orang. Makna kemerdekaan bisa digali dari sini. Nenek moyang
orang leragere memandang kampung halamannya sebagai wilayah merdeka. Pandangan tersebut
kemudian diwujudkan melalui pendirian
yang kokoh dan kemauan keras untuk menentang penjajahan. Buktinya bisa digali
dari peristiwa Tiwa Ua. Melalui peristiwa heroik ini nenek moyang orang Leragere membuktikan
dirinya sebagai manusia merdeka yang berhak penuh atas kampungnya sendiri.
Sejak dulu orang
Leragere sudah mengenal persatuan dan kesatuan. Yang tidak hanya sebatas kampung sendiri tetapi
mencakup seluruh wilayah etnis Leragere. Hal ini bisa digali melalui filosofi “Nobo buto.” Arti lurusnya
adalah delapan tempat duduk batu. Filosofi ini lahir dari semangat
persatuan kesatuan antara delapan kampung seetnis dan budaya musyawarah mufakat.
Untuk memecahkan
berbagai persoalan yang mengganggu hayat hidup bersama biasanya diadakan rapat
besar yang disebut tobo baung. Rapat
ini dihadiri para tetua dari delapan kampung etnis Leragere yakni : Lewoeleng,
Lewolera, Ledoblolong, Atakowa, Lewotaa, Lewodoli, Lewoheba dan Balurebong.
Tempat pelaksanaan rapat umum di Leramau.
Sebuah lapangan terbuka di tengah kampung Ledoblolong. Pada masa setelah
Indonesia merdeka lapangan tersebut difungsikan sebagai lokasi pasar barter.
Tempat pertemuan para pelaku pasar dari Leragere, Leralodo, Lamalera, Kedang, Ileape dan Hadakewa. Di tengah
lapangan leramau terdapat sebatang pohon beringin. Di sekeliling pohon besar ini
dipasang delapan tempat duduk atau nobo
dari batu ceper. Ketika diadakan musyawarah nobo ini akan ditempati oleh
masing-masing kepala kampung. Pemberian tempat istimewah kepada kepala kampung
merupakan bentuk kedaulan dengan perwakilan yang bersifat sangat hakiki. Suara
kepala kampung dianggap mewakili suara dari semua warga kampungnya. Pada
konteks ini juga Kepala kampung diterima sebagai pemimpin yang mampu mewujudkan
keadilan serta kemakmuran bagi warganya.
Budaya persatuan
serta musyawarah mufakat pada tingkat keluarga dan suku bisa digali melalui ungkapan : Muh’pu
han’i, ame rago a’ang pulo a’ring lema aho manung bineng lame. Ungkapan tersebut
ditujukan pada aktifitas atau tindakan mengumpulkan segenap anggota keluarga
atau suku guna membicarakan hal penting. Tujuan utamanya berupa tercapai kata
sepakat yang dikenal melalui ungkapan : Gui
tang uing, pudung tang mudung. Perkembangan peradaban sekarang yang cendrung memberi ruang bagi tumbuh
suburnya sikap individualistik membuat budaya positif persatuan kesatuan serta
musyawarah keluarga makin hari makin pudar. Mestinya setiap keluarga di Leragere berperan
aktif dalam mempertahankan nilai positif budaya lokal terkait rasa hormat, persatuan kesatuan dan
gotong royong.
Keluarga
dan Gotong royong
Sosiolog
Koentjaraningrat (1971) memandang gotong
royong sebagai bentuk kerjasama antar keluarga yang diwariskan turun temurun.
Kebiasaan ini tercatat sebagai salah budaya nasional yang sangat membantu meringankan pekerjaan. Dalam tradisi Lamaholot
kegiatan gotong royong dikenal dengan sebutan gemohing (B.K. Koten 1983). Tradisi ini biasa diterapkan dalam
kegiatan-kegiatan seperti membuka ladang, menanam, menyiang dan memanen. Bentuk
non tenaga manusianya terlihat pada kegiatan kumpulan uang atau barang.
Sejak dulu
orang leragere juga sudah mengenal dan menerapkan dengan baik sistim gotong
royong. Dalam kegiatan ladang dikenal
dengan sebutan pong mupu.
Masing-masing suku atau kampung membentuk kelompok kerja. Tugas kelompok
tersebut adalah menyelesaikan pekerjaan milik anggota. Jata masing-masing
anggota diatur secara bergilir. Anggota yang berhalangan hadir pada jadwal yang
telah disepakati wajib memenuhi kealpaannya. Gotong royong dalam kegiatan
perladangan ini bisa di gali dari penggalan syair : Seda brene-brene, nereng bote awo pahti; hodi tahpang lima waing preto
ubu brete. Makna tersirat dari syair ini adalah pekerjaan ladang yang berat
bisa jadi ringan bila ditangani bersama-sama.
Bentuk gotong
royong lain dari masyarakat etnis Leragere
juga terlihat pada kegiatan yang dikenal
dengan sebutan : Taling tu’lung, poh’ta
bor’a. Merupakan suatu bentuk kegiatan membantu memenuhi atau melengkapi
kekurangan kerabat. Nampaknya seperti arisan tetapi tidak mewajibkan keluarga
yang ditolong untuk membalasnya. Meski demikian keluarga terbantu tetap
memiliki beban moril untuk membalasnya di kelak kemudian hari. Tentang ini bisa
digali dari ungkapan : Lerong bo gonu,
bulong monu; Hee nung tea lahka monu di tea. Arti lurusnya : Hari ini saya,
besok giliran kamu; Siapa punya sudah tidak ada maka kamu punya juga tidak ada.
Ketika segala
sesuatu dinilai dengan uang maka budaya gotong royong lambat laun mulai
kehilangan makna. Bantuan dalam bentuk barang atau uang dicatat sebagai hutang
yang wajib dilunaskan. Perubahan ini bisa membuat orang yang menerima bantuan
menjadi tertekan. Mungkin saja saat tempo pembayaran tiba yang bersangkutan
dalam kondisi tidak mampu. Pada gotong royong menyelesaikan pekerjaan sekarang
ini nilai tenaga kerja mulai dihargai dengan upah. Akibatnya keluarga yang
kurang mampu mungkin tidak pernah merasakan manfaat gotong royong tersebut.
Jatanya selalu diserahkan ke pihak lain yang mampu membayar. Bila nilai gotong
royong dalam arti sebenarnya dihidupkan kembali maka urusan pendidikan anak menuju generasi penerus berkwalitas makin meningkat.
Keluarga
dan Pendidikan Anak
Sejak
dulu masyarakat etnis Leragere telah memahami tentang pentingnya pendidikan
anak dalam sebuah keluarga. Sangat disadari bahwa pengetahun dan ktrampilan
merupakan bekal hidup anak kelak setelah membentuk rumah tangga sendiri. Pada
masa sebelum ada sekolah tugas
pendidikan anak ditangani sendiri oleh orang tua, kerabat dan para
tetua. Peran ini bisa digali melalui ungkapan : Ina tube panu, ama nuru nuan; mo hodi hea, tou tele; saga mu lima, saga
mu lei; saga mu nara,saga mu su’u la’ma le’lang a’lang. Arti harafiahnya,
ajaran orang tua layak kau terima, jaga kaki, jaga tangan, jaga nama, suku dan kampung
halaman. Bahwa tidak ada orang tua yang
mau supaya anaknya gagal di kemudian hari.
Pendidikan
anak pada tempo dulu lebih bersifat praktis dan mengakar, tidak terikat waktu,
tempat dan biaya. Cakupan pembelajaran
anak hanya sebatas pengetahuan kealaman termasuk dunia gaib dan ketrampilan
teknis. Meski demikian ukuran ketercapaian belajarnya sangat tinggi dibanding
target capaian belajar sekarang. Pada masa sebelum orang mengenal huruf ini seorang anak laki-laki baru
dianggab berhasil bila mampu membuka kebun baru, mengiris tuak dan membangun
lumbung. Sedangkan anak perempuan harus bisa memasak, memintal benang dari
kapas, mengikat motif dan menenun sarung.
Mengakarnya
pendidikan di masa-masa sulit juga terlihat pada tingkat kepatuhan anak
terhadap orang yang lebih tua, kemandirian dalam memecahkan masalah hidup dan
pelanggaran atas norma susila. Kondisi tempo
dulu ini ternyata sangat bertolak belakang dengan kenyataan sekarang. Ketergantungan anak pada orang tua
sangat tinggi, rasa hormat terhadap yang lebih tua kurang nampak dan
pelanggaran norma susila makin melonjak. Menjadi pertanyaan Apakan ini disebabkan karena orang tua dan
guru salah mendidik ataukah sistem teknisnya tidak sejalan lagi dengan kemajuan
peradaban ?
Pola
pendidikan anak dan kemajuan peradaban itu ibarat keping mata uang. Dua muka
dengan corak berbeda tetapi harus tetap utuh dalam satu lingkaran. Bila pola
pendidikan yang diterapkan tidak seiring lagi dengan kemajuan peradaban maka
akan timbul retak atau pecah pada bagian-bagian tertentu. Keinginan untuk
menyesuaikan diri dengan kemajuan peradaban
akan menghasilkan lompatan-lompatan tidak beraturan. Pada kondisi
seperti ini yang paling merasakan akibatnya adalah anak.
Kenyataan
sosial sekarang seperti pengangguran tenaga kerja terpelajar, mahalnya biaya
pendidikan dan budaya hidup mewah termasuk faktor yang membatasi kemauan orag
tua untuk menyekolahkan anaknya. Banyak orang tua berprinsip bahwa untuk apa
sekolah tinggi-tinggi kalau pada
akhirnya jadi penganggur. Jika ditelusuri lebih jauh sesungguhnya prinsip ini
muncul karena merasa tidak mampu menanggung biaya pendidikan. Boleh jadi
perasaan tersebut lahir dari tekanan budaya hidup mewa, menguatnya sifat
indifidualistik dan lunturnya semangat gotong royong.
Penutup
Kemajuan
suatu wilayah sangat ditentukan oleh daya dukung keluarga pembentuknya. Bila
keluarga sejahtera dan memelihara baik budaya positif rasa hormat, persatuan,
dan gotong royong maka akan tercipta sistem
sosial yang kuat, terstruktur dan tertata baik. Penyakit peradaban maju seperti
sikap individualistik, ketaatan semu dan
budaya hidup mewah dapat dicegah.
DFTAR REFRENSI
Koentjaraninggrat. 2009. Ilmu Antropologi. Renaka Cipta Jakarta
Koten K. B. 1971, Timbulnya Kepercayaan Asli Masyarakat
Lewolema (Skripsi) FKIP, Undana Kupang
Paul B. Horton. 1987. Sosiologi,.Erlangga.
Jakarta

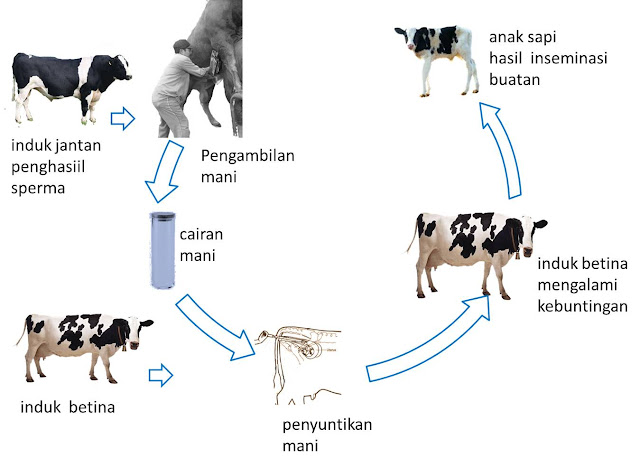

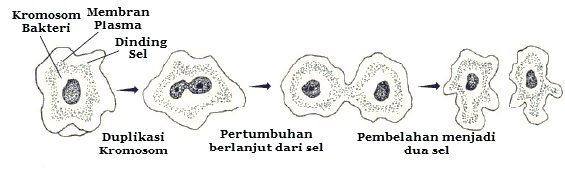
Komentar
Posting Komentar